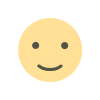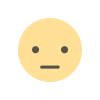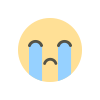OPINI: Beban Berat KPU dan Parpol Pasca Upnormalisasi Pilkada
Oleh: Dr. Noviardi Ferzi, SE. MM Lazimnya UU atau peraturan yang melahirkan strategi, namun dalam revisi UU Pemilu kali ini, sebuah strategi tampaknya lahir terlebih dulu. Hanya untuk kepentingan politik 2024, hasilnya pembahasan UU pemilu pun terpaksa berhenti. Mirip praktek "Aborsi" yang mengugurkan UU yang bakal lahir. Sebuah personifikasi gamblang tentang up normalisasi yang terjadi.

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi, SE. MM
Lazimnya UU atau peraturan yang melahirkan strategi, namun dalam revisi UU Pemilu kali ini, sebuah strategi tampaknya lahir terlebih dulu. Hanya untuk kepentingan politik 2024, hasilnya pembahasan UU pemilu pun terpaksa berhenti. Mirip praktek "Aborsi" yang mengugurkan UU yang bakal lahir. Sebuah personifikasi gamblang tentang up normalisasi yang terjadi.
Sebelumnya dalam prolegnas prioritas 2021 di Baleg DPR RI, tidak ada satupun fraksi di DPR menyatakan keberatan atau memberikan catatan terhadap RUU Pemilu.
Namun hal ini berubah ketika pemerintah menyatakan sikapnya untuk mengelar pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Pada saat itu partai-partai mulai berbalik arah dari yang tadinya semangat untuk merevisi UU tersebut, untuk kemudian bersepakat untuk tidak membahasnya lagi.
Hasilnya kini partai politik (parpol) mulai menghitung langkah mereka setelah mengubah sikap terhadap RUU Pemilu. Karena paska dihitung-hitung apa yang kemudian gagal direvisi itu, terkait strategi apa yang akan diambil untuk pemenangan partai mereka.
Meski sebenarnya perubahan sikap partai politik setiap pembahasan revisi UU Pemilu adalah hal yang biasa. Banyak hitungan masing-masing partai yang dipaksakan agar kepentingannya diakomodasi.
Masing-masing partai mulai melakukan perhitungan peluang yang mereka bisa peroleh dengan rencana revisi UU Pemilu termasuk melihat peluang menyatukan UU Pilkada sekaligus dalam UU Pemilu.
Terlepas dari itu, sikap sejumlah fraksi di DPR RI dan pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) patut untuk dipertanyakan.
Apalagi alasan pemerintah yang tak ingin ada revisi UU Pemilu karena situasi pandemi Covid-19. Padahal, UU Pemilu justru harus direvisi untuk menyediakan kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan di tengah kondisi bencana non alam seperti pandemi Covid-19.
Pada sisi yang lain kita juga patut menyayangkan sikap beberapa partai politik di DPR yang menolak revisi UU pemilu karena mengikuti sikap pemerintah. Seharusnya, DPR menjadi penyeimbang arah kebijakan kekuasaan. Bukan begitu saja menuruti kemauan pemerintah, apalagi ada dugaan jika revisi UU Pemilu dibatalkan hanya karena kepentingan segelintir pihak terkait kontestasi politik.
Tentu saja kegagalan revisi undang-undang ini menjadi tbeban penyelenggara pemilu yang cukup berat seperti dalam Pemilu 2019 dengan lima kotak suara. Saat pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan sekaligus.
Konsekuensinya penyelenggara dalam hal ini KPU hingga partai politik akan menghadapi beban berat, meski nanti ada perubahan desain keserentakan pada Pemilu 2024 mendatang. Dimana beban keserentakan itu ada pada irisan tahapan yang berimpitan antara pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
Sebagai gambaran jika tak ada perubahan, Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar pada April, sedangkan pilkada pada November, rentang ini lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 yang berjarak sepuluh bulan dari Pilkada 2018.
Tahapan pemilu akan berlangsung sejak dua tahun sebelum hari pencoblosan suara, sedangkan pilkada satu tahun. Begitu pula kebutuhan pembiayaan akan bersifat multi years, baik APBN maupun APBD.
Kompleksitas irisan yang berimpitan ini yang semestinya dihitung oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berkaca dari proses ini seolah membuat kita sadar, bahwa seolah konsep demokrasi hanya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang, sebaliknya, siapa yang lemah dia yang akan tergerus.
Sehingga tak berlebihan jika lahir penilaian bahwa demokrasi Indonesia sekarang bergantung pada kekuatan baru, yakni kekuatan uang dan modal, dibanding nilai dan cita - cita mulia membangun bangsa, jauh dari kepentingan kelompok yang mengemuka. (*)


 Ari W
Ari W